JAKARTA – Korporasi di Asia Pasifik dinilai tidak memiliki kemajuan yang berarti dalam hal aksi iklim, demikian menurut studi yang dilakukan oleh firma akuntan dan konsultan EY.
Lambatnya kemajuan itu terjadi ketika akselerasi diperlukan guna memenuhi tujuan Perjanjian Paris dan menahan pemanasan global di tingkat 1,5 derajat Celsius.
“Sustainable Value Study 2023 menunjukkan bahwa di Asia Pasifik gerakannya melambat, sementara kondisi sedang genting. Pencapaian net zero menjadi lebih sulit,” ujar EY seperti dilansir dari South China Morning Post, Minggu (31/12/2023).
Survei ini dilakukan antara Agustus dan Oktober terhadap 520 manajer setingkat chief sustainability officer di perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pendapatan tahunan minimal US$1 miliar di 10 industri di 23 negara.
Sekitar sepertiga dari responden berasal dari perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik dari berbagai industri. Dari jumlah tersebut, 28 persen berada di China, diikuti oleh 24 persen di Jepang dan Australia.
Sekitar 65 persen perusahaan di kawasan ini akan mengeluarkan dana yang sama atau lebih sedikit untuk mengatasi perubahan iklim dalam 12 bulan ke depan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, demikian hasil survei tersebut.
Seperlima dari para pemimpin keberlanjutan perusahaan di kawasan ini mengatakan bahwa biaya finansial untuk mencapai komitmen perubahan iklim perusahaan terlalu tinggi sehingga membuat mereka mengundurkan targetnya. Angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari rasio organisasi yang mengatakan hal yang sama di Amerika, Eropa, Timur Tengah, India, dan Afrika.
Hanya 15 persen dari responden di Asia Pasifik yang mengatakan bahwa perusahaan mereka berkomitmen untuk mencapai ambisi perubahan iklim pada 2030 atau lebih awal, sementara 19 persen lainnya mengatakan bahwa target mereka adalah pada 2060 atau lebih. Sisanya menetapkan target antara 2030 dan 2060.
Secara global, tahun target rata-rata telah bergeser ke tahun 2050 dari tahun 2036 pada studi tahun sebelumnya, yang menyurvei sekitar 500 perusahaan dengan menggunakan metodologi yang konsisten dan demografi peserta.
“Ada banyak faktor di balik penundaan ini, termasuk fakta bahwa semakin banyak pekerjaan yang telah dilakukan perusahaan untuk memenuhi target, semakin jelas bahwa pencapaian tujuan akan memakan waktu, terutama karena adanya pembatasan waktu yang diberlakukan untuk meluncurkan [proyek energi] terbarukan dan mengurangi emisi,” kata Terence Jeyaretnam, pemimpin layanan perubahan iklim dan keberlanjutan EY Asia Pasifik.
Menurut Jeyaretnam, banyak perusahaan baru memahami sepenuhnya cakupan tantangan regulasi, keuangan, teknologi, atau data-sentris ketika mereka mulai mengimplementasikan rencana keberlanjutan mereka, ujarnya.
“Terkadang komitmen net zero awal dibuat oleh pemimpin keberlanjutan, bahkan CEO, yang tidak selalu memiliki penilaian terhadap elemen komersial yang diperlukan,” ujar Jeyaretnam.
Sementara itu, studi pengungkapan risiko iklim (climate risk disclosure) tahunan kelima yang dilakukan oleh EY menemukan bahwa hanya 26 persen dari 1.536 perusahaan di 13 sektor di 51 yurisdiksi yang telah menyertakan dampak kuantitatif dari risiko terkait iklim dalam pengungkapan publik mereka.
Bursa saham di sebagian besar pusat keuangan utama diperkirakan akan mengadopsi pengungkapan tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Di Hong Kong, pengungkapan tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025.
“Tinjauan global terhadap pengungkapan terkait iklim hanya menunjukkan perkembangan tambahan dalam kualitas pelaporan iklim, yang berimplikasi pada kemampuan perusahaan untuk menarik investasi hijau,” ujar EY.
Di Asia Pasifik, perusahaan-perusahaan Jepang mendapatkan nilai tertinggi yakni 59 dari 100 untuk kualitas pengungkapan, dibandingkan dengan 58 untuk perusahaan-perusahaan Korea Selatan, 36 untuk perusahaan-perusahaan India, dan 30 untuk perusahaan-perusahaan China. (TR)





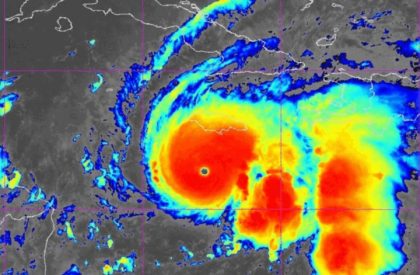












Komentar