JAKARTA – Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu persoalan yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Rilus A. Kinseng Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB University Bogor secara tajam menyoroti industri ekstraktif itu.
Menurutnya, kegiatan pertambangan sangat berbeda dengan pertanian yang sudah dikuasai oleh komunitas secara turun-temurun. Kegiatan pertambangan memerlukan pengetahuan dan skill yang baru, dan bahkan kekuatan fisik yang juga berbeda dengan kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak warga komunitas yang kehilangan pekerjaan ketika lahan pertanian mereka dikonversi menjadi lahan pertambangan. Tentu saja ini menyebabkan porak poranda kehidupan mereka yang kehilangan tanah dan tanaman yang merupakan sumber penghidupan mereka.

Demikian disampaikan oleh Rilus dalam kapasitanya selaku Ahli Pihak Terkait Idrus dkk, dalam sidang uji Materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada Selasa (5/12/2023) lalu di Ruang Sidang Pleno MK.
Konflik Sosial di Pulau Wawonii
Rilus menjelaskan konflik sosial yang dipicu kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii. Konflik sosial itu awalnya adalah konflik vertikal antara komunitas lokal dengan pihak perusahaan. Namun, konflik sosial yang terjadi bukan hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal antarsesama warga, yakni antara warga yang pro kegiatan pertambangan dan yang kontra. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) telah memecah belah komunitas lokal, yang sebenarnya masih bersaudara. Jika merujuk pada teori konflik Dahrendorf, kelompok masyarakat yang terbelah tersebut bukan hanya sebatas “quasi groups”, tetapi sudah menjadi “conflict groups” (Dahrendorf, 1958 dan Wallace and Wolf, 2006).
“Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT GKP di Pulau Wawonii ini tidak memenuhi syarat yang dinyatakan pada huruf k tersebut. Kegiatan pertambangan oleh PT GKP di Pulau Wawonii ini nyata-nyata telah “merugikan masyarakat sekitarnya” secara sosial, ekonomi, dan lingkungan/ekologis. Selain mengganggu bahkan memporak poranda livelihood sebagian warga, kegiatan pertambangan ini telah merusak keharmonisan dan kohesi sosial masyarakat setempat,” terangnya.
Rilus menegaskan, syarat yang dikemukakan dalam Pasal 53 huruf k UU PWP3K itu sangat sesuai dan sejalan dengan perkembangan terkini terkait kegiatan pembangunan apapun, termasuk kegiatan pertambangan. Oleh sebab itu, harus tetap dipertahankan, tidak boleh dibatalkan.
Diskriminasi dan Marjinalisasi
Menurut Rilus, pembatalan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 U PWP3K ini justru berpotensi menyebabkan diskriminasi dan marjinalisasi komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan pembangunan seperti yang seringkali terjadi selama ini. Bahkan dalam beberapa kesempatan Rilus pernah mengingatkan bahwa sejauh ini masyarakat pesisir masih berada di posisi yang lemah dan sering tergusur, termasuk masyarakat adat dan masyarakat tradisional sehingga perlu kebijakan afirmatif.
Rilus pun menjelaskan, komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil sering kali mengalami marjinalisasi akibat kehilangan kontrol dan akses terhadap sumber daya alam, baik sebagai tempat berkerja/berusaha maupun sebagai tempat pemukiman. Mereka sangat memerlukan perlindungan.
“Salah satu instrumen yang dapat memberi perlindungan bagi mereka adalah UU PWP3K Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2. Kedua pasal ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal mana pun dari UUD 1945. Sebaliknya, pembatalan kedua pasal ini justru membuka peluang terjadinya diskriminasi, marjinalisasi, bahkan penindasan terhadap warga komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, utamanya oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan besar, seperti penguasa dan pengusaha. Oleh sebab itu, kedua pasal ini harus tetap dipertahankan,” tegasnya.
Sementara DPR yang diwakili oleh Wihadi Wiyanto selaku anggota Komisi XI menyampaikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah bagian dari wilayah yang dikuasai negara yang harus dijaga kelestariannya. Negara perlu mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk melindungi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologinya. Industrialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sering memarjinalisasi penduduk setempat sehingga perlu pengaturan yang adil.
Dimaknai Lebih Tegas
Sedangkan Charles Simabura yang juga Ahli Pihak Terkait Idris menjelaskan, keberadaan Pasal 35 huruf k telah menimbulkan ketidaksinkronan pengaturan dengan Pasal 23 maka sudah sepatutnya pasal a quo harus dimaknai bertentangan dengan konstitusi karena membuka ruang pemanfaatan pulau kecil untuk kegiatan lain dalam hal ini penambangan mineral.
“Untuk memenuhi kepastian hukum, landasan filosofis, sosiologis, tujuan dan asas-asas undang-undang a quo, maka rumusan Pasal 35 huruf k harus dimaknai secara lebih tegas dengan menghilangkan frasa “apabila” dan rumusan pasal selanjutnya. Dengan demikian, dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral,” tegas Charles.
Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Sebagai tambahan informasi, permohonan Nomor 35/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K ini diajukan oleh PT. Gema Kreasi Perdana yang diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama). Pemohon merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil, terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP-PPK.
Pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung sebagai larangan tanpa syarat untuk melakukan kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong Pulau Kecil. Padahal Pemohon telah memiliki ijin yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel di wilayah tersebut. Bahkan Ijin Usaha Pertambangan milik Pemohon telah mengalami beberapa kali perubahan dari Ijin semula berupa Kuasa Pertambangan Nomor 26 Tahun 2007 yang terbit sebelum berlakunya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Sehingga menurut Pemohon, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP-PPK bila ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat, maka seluruh tata ruang terhadap Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur oleh Peraturan Daerah akan bertentangan dengan UU tersebut dan harus dilakukan perubahan. Akibatnya, seluruh perusahaan yang berusaha di bidang pertambangan di wilayah-wilayah tersebut harus dihentikan pula. Tentu hal ini akan merugikan banyak perusahaan tambang, dan sama halnya dengan Pemohon. Padahal perusahaan-perusahan tambang telah melaksanakan kewajiban pembayaran kepada negara. (MK)



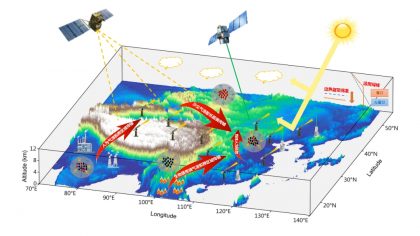











Komentar