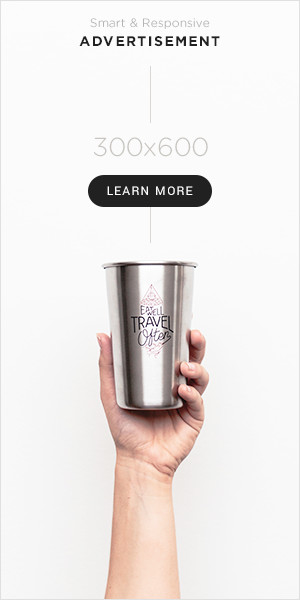JAKARTA – Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asep Hidayat menekankan peran strategis kajian ilmiah dalam mendukung konservasi keanekaragam hayati di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Jamming Session Seri 1 Tahun 2025, dengan bertema “Konservasi dan Pemanfaatan Tumbuhan Khas Indonesia”, yang digelar secara daring, Kamis (24/4). Kegiatan itu diinisiasi oleh Kelompok Riset Autekologi Flora Endemik dan Dilindungi (AFEL) serta Kelompok Riset Autekologi Flora Perdagangan.
Asep menyebutkan bahwa kajian ilmiah dalam konservasi, tidak berdampak secara instan. Namun demikan, jika dimanfaatkan secara tepat bisa mempunyai pengaruh yang sangat besar.
“Konservasi bukan hanya soal pelestarian, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola kekayaan hayati ini secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis pengetahuan, teknologi modern, dan kearifan lokal,” ujarnya.
Asep juga menyoroti ancaman seperti alih fungsi lahan, deforestasi, dan perubahan iklim menjadi tantangan nyata, sehingga upaya konservasi yang terintegrasi dan berkelanjutan adalah hal yang penting untuk dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor berbasis data ilmiah. Menurutnya, ribuan spesies tumbuhan khas Indonesia bersifat endemik, langka, dan memiliki nilai ekologis, ekonomis, serta budaya yang tinggi.
“Keberadaan flora kita sedang menghadapi tekanan besar mulai dari deforestasi, konversi lahan, perambahan hutan, hingga perubahan iklim. Sehingga, tak sedikit spesies kini berada di ambang kepunahan,” ungkapnya mengingatkan.
Maka dari itu, lanjut Asep, dibutuhkan ruang strategis untuk mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi.
“Meski forum ini bersifat informal, tujuannya jelas: mendorong kolaborasi, memperkaya pengetahuan bersama, dan memetakan arah riset serta inovasi, khususnya terkait konservasi dan pemanfaatan tumbuhan khas Indonesia, seperti Nepenthes ataupun spesies lain yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi,” jelasnya.
Asep berharap, forum ini dapat melahirkan inovasi dan rekomendasi konkret yang memperkuat kebijakan konservasi serta mendorong pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Ketua Forum Pohon Langka Indonesia (FPLI), Tukirin Partomihardjo menyampaikan tantangan dalam konservasi tumbuhan khas Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari konservasi adalah tidak hanya melestarikan keanekaragaman hayati, namun juga menjaga sistem pendukung kehidupan sekaligus memastikan pemanfaatannya yang berkelanjutan.
“Dari kurang lebih 6.500 spesies tumbuhan yang sudah dikaji statusnya, 21,4% tumbuhan terancam punah, 1 jenis sudah punah dan 2 jenis punah di alam, sedangkan pemerintah baru menetapkan 116 spesies atau 13% tumbuhan”
Tukirin menekankan pentingnya konservasi tumbuhan khas Indonesia sebagai langkah terpadu untuk menjaga kelestarian dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia menyoroti bahwa strategi konservasi perlu mencakup perlindungan habitat, pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, dan restorasi lahan terdegradasi. Pada akhir paparannya, ia menekankan pentingnya kerjasama berbagai stakeholder, akademisi, peneliti dan masyarakat untuk penyelamatan pohon langka di Indonesia.
Sementara itu, pembicara kedua, Muhammad Mansur, Peneliti PREE menyampaikan hasil-hasil penelitiannya yang sudah dilakukan lebih dari 30 tahun mengenai “Keanekaragaman Nepenthes di Pulau Sumatra, status konservasi dan budidayanya”.
“39 spesies Nepenthes atau yang juga dikenal sebagai kantung semar dapat ditemukan tersebar di dataran tinggi maupun rendah di Pulau Sumatera. 33 spesies diantaranya adalah spesies endemik, 5 jenis Critically Endangered dan 3 jenis Endangered. Hampir semua jenis Nepenthes dilindungi oleh undang-undang, namun Nepenthes juga merupakan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar nasional maupun internasional, karena bentuknya yang unik,” rinci Mansur.
Pembicara selanjutnya, Tika Dewi Atikah, Peneliti PREE memaparkan mengenai “Potensi Jenis-jenis Tumbuhan yang Diperdagangkan”, ia menyoroti beberapa jenis tumbuhan yang bernilai ekonomi tinggi dan aktif diperdagangkan, seperti spesies penghasil gaharu (Aquilaria sp.) dan Dalbergia parviflora atau akar laka.
“Salah satu hasil penelitian di Pulau Buru menunjukkan rata-rata biomassa Aquilaria sp. mencapai 600,5 kg per hektar, menunjukkan potensi ekonominya yang signifikan,” ungkapnya.
Selain itu, ia memaparkan bahwa Dalbergia parviflora (akar laka), tumbuhan yang digunakan sebagai bahan dupa dan obat, masih banyak diperdagangkan, khususnya kayu yang telah mati dan lapuk.
“Sedikitnya 1.300 warga di tiga kabupaten di Kalimantan Tengah terlibat dalam rantai perdagangan akar laka. Ini menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat,” terang Tika.
Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan pendekatan sosial untuk mengelola perdagangan spesies bernilai tanpa mengabaikan aspek konservasinya.
Sementara itu, Joeni S. Rahajoe, Peneliti PREE memaparkan hasil kajian timnya di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“Kami mencatat ada 95 jenis tanaman bermanfaat yang digunakan masyarakat di sekitar IKN. Sekitar 58,7% diantaranya merupakan spesies asli Kalimantan,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan penanaman yang diterapkan masyarakat di wilayah ini memadukan spesies lokal, non-lokal bernilai ekonomi, dan spesies dari Daftar Merah IUCN, seperti Durio kutejensis, Baccaurea lanceolata, dan Aquilaria microcarpa. Sistem agroforestri tersebut tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menyimpan karbon, dengan rata-rata cadangan karbon mencapai 33,28 Mg C/ha.
“Pendekatan ini memberi manfaat ganda ekonomi sekaligus konservasi,” ujarnya.
Kekayaan tumbuhan Indonesia dengan tingkat endemisitasnya yang tinggi, menjadikannya sangat penting untuk dilestarikan. Sayangnya, banyak diantaranya terancam punah, sehingga dukungan riset yang dapat mengungkapkan manfaat dan nilai tambahnya sangat penting untuk dilakukan. BRIN mendorong riset berbasis lapangan dan laboratorium bekerjasama dengan berbagai stakeholder dan dan keterlibatan masyarakat lokal sebagai kunci untuk memastikan konservasi dan pemanfaatan berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. (TR Network)