JAKARTA – Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan, telah berakhir, Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai COP29 gagal menghasilkan keputusan untuk mencegah perluasan dampak buruk krisis iklim.
Ambisi penurunan emisi global jauh dari harapan, komitmen pendanaan iklim negara maju tak kunjung terealisasi, serta kesepakatan pasar karbon justru berpotensi memperparah ancaman terburuk kerusakan dan kehilangan akibat krisis iklim bagi negara berkembang, pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelompok rentan.
“Hasil COP29 menunjukkan negara-negara maju telah gagal merevisi target pengurangan emisi. Tidak ada satupun negara yang berani menjadi pionir dalam memimpin penurunan emisi yang lebih tajam. Kondisi ini meningkatkan risiko suhu bumi rata-rata melampaui 1.5 derajat celcius,” kata Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Selasa, 3 Desember 2024.
Menyitir laporan The Carbon Majors Database (Carbon Majors, 2024), sejak Perjanjian Paris ditetapkan, laju emisi bahan bakar fosil justeru semakin tak terkendali. Secara historis, 78 entitas perusahaan bertanggung jawab atas pelepasan 70% total emisi CO2 global. Entitas perusahaan didominasi oleh negara-negara produsen di Amerika Serikat, China, Rusia dan Timur Tengah.
Pelepasan emisi global dikontribusikan secara tidak proporsional oleh sejumlah emitter, yang mengeskalasi pemanasan suhu global bumi. Mereka mendapat keuntungan ekonomi berlipat, sementara pada saat yang sama, bumi dan milyaran manusia harus menanggung ancaman dan dampak terberatnya. Sayangnya, COP29 justru menegasikan hutang ekologis negara-negara maju dan korporasi dalam reparasi iklim, dengan mengabaikan transisi ambisius bahan bakar fosil dan alokasi pendanaan iklim berkeadilan bagi negara-negara berkembang.
“Perundingan program kerja mitigasi di COP29 mengalami kemunduran dibandingkan COP28. Komitmen untuk “beralih dari bahan bakar fosil” (move away from fuels) dihilangkan, sementara bahan bakar fosil justru mendapat tempat. Situasi ini membuka peluang bagi perkembangan teknologi solusi sesat, mengancam investasi dan pemborosan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk transisi energi yang berkeadilan,” ujar Syaharani, Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim ICEL.
Kegagalan pendanaan iklim yang berkeadilan telah memperlebar kesenjangan dan membahayakan kelompok rentan. Syaharani mengingatkan bahwa ”Janji negara maju untuk menyediakan dana iklim sebesar US$300 miliar dari sumber publik masih jauh dari kebutuhan riil sebesar US$2.5 triliun. Target US$1.3 triliun yang diharapkan tercapai pada tahun 2035 pun berpotensi menjadi beban utang bagi negara-negara miskin dan berkembang.”
Ironisnya, pasar karbon justru diusulkan sebagai bagian dari skema pembiayaan, semakin mengabaikan prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) yang seharusnya meringankan beban negara-negara miskin dan berkembang. Ketidakpastian aliran dana tanpa syarat ini memperluas dampak buruk perubahan iklim dan semakin membahayakan kelompok rentan yang memiliki kapasitas adaptasi terbatas.
Kelompok Rentan di Indonesia Kian Terancam
Indonesia memiliki >17.000 pulau yang rawan tenggelam akibat dampak perubahan iklim. Namun, ARUKI menilai Hasil COP29 tidak cukup mengalokasikan kepentingan dan kebutuhan yang memadai bagi negara-negara berkembang, pesisir serta pulau-pulau kecil untuk beradaptasi terhadap dampak krisis iklim. Subjek masyarakat adat, petani, nelayan tradisional, perempuan, ragam penyandang disabilitas, orang muda, serta kelompok miskin kota, semakin dijauhkan dari tujuan-tujuan perundingan global iklim.
“COP29 mengabaikan komitmen pendanaan publik yang konkret untuk adaptasi. Meskipun teks negosiasi menyebutkan adanya pembiayaan adaptasi, proporsinya tidak jelas, meninggalkan negara-negara berkembang dalam ketidakpastian menghadapi dampak perubahan iklim. Dana hutang iklim semakin membebankan negara-negara berkembang, baik secara fiskal, sosial dan ancaman terhadap subjek rentan,” kata Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan.
Situasi ini, lanjut Arma, berdampak langsung pada kelompok rentan yang paling membutuhkan dukungan adaptasi untuk melindungi diri dari dampak perubahan iklim.
“Diperparah keterbatasan sumber daya, krisis iklim telah membebani perempuan dengan ancaman terhadap perampasan tanah, mata pencaharian, dan masa depan mereka. Parahnya, proyek iklim sesat —seperti geothermal di Poco Leok, Mataloko, dan Gunung Rajo Basa, serta PLTA di Poso—justru menimbulkan kerusakan signifikan pada ruang hidup dan penghidupan masyarakat, yang dampaknya paling terasa bagi perempuan.
Pada bagian lain, kesepakatan tentang mekanisme pasar karbon, yang seharusnya menjadi upaya terakhir, justru dicapai lebih dulu, diiringi kaburnya komitmen penurunan emisi dan pendanaan dari negara maju. Kepentingan energi fosil diperpanjang.
“Dokumen IPCC Synthesis Report 2023 menunjukkan bahwa dalam berbagai skenario, penduduk kelahiran 1980-2020 dihadapkan dengan kenaikan suhu lebih tinggi 0,5-3°C dibandingkan penduduk kelahiran 1950-1980 semasa hidupnya. Artinya, ancaman krisis iklim semakin memperparah kehidupan orang muda,” kata Ginanjar Aryasuta, Koordinator Climate Ranger Jakarta.
Pada saat intensitas bencana iklim meningkat, ragam penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi dan hambatan struktural berlapis.
“Hasil studi Perhimpunan Jiwa Sehat pada 2024 menunjukkan bahwa, ketika bencana iklim melanda, penyandang disabilitas sering kali menjadi korban berlapis dengan tingkat kematian empat kali lebih tinggi akibat kurangnya akses dan dukungan yang inklusif,” kata Nena Hutahaean dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS).
COP 29 berakhir dengan kekecewaan mendalam. Kegagalan negara-negara maju dalam menunjukkan komitmen nyata untuk mengatasi krisis iklim mengancam masa depan planet ini dan menempatkan kelompok rentan pada risiko yang lebih besar, mengabaikan prinsip keadilan iklim yang seharusnya menjadi landasan utama.
“Pemerintah Indonesia harus lebih ambisius dalam menangani krisis iklim yang adil, menghentikan skema-skema utang dan bisnis atas nama krisis iklim, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan iklim. ARUKI menekankan RUU Keadilan Iklim harus mampu membawa keadilan bagi lingkungan, menegakkan hak asasi manusia, dan melindungi kelompok rentan yang mengalami kerugian akibat dampak krisis iklim,” tutup Torry Kuswardono. (TR Network)





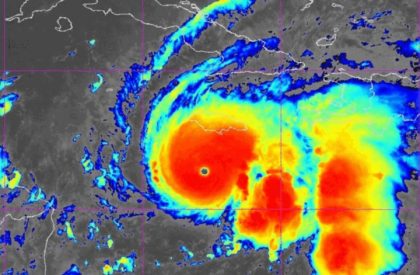











Komentar