Di tengah upaya besar Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan, transisi energi terbarukan, dan memajukan sektor pariwisata, terdapat sebuah pertanyaan mendasar yang seringkali terlupakan: siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek-proyek ini, dan siapa yang harus menanggung konsekuensinya? Proyek seperti Food estate, Bioethanol, proyek transisi energi terbarukan, dan pariwisata super prioritas yang digalakkan oleh pemerintah seringkali digambarkan sebagai kemajuan yang membawa manfaat bagi seluruh bangsa. Namun, jika kita menilai lebih dalam dengan menggunakan pendekatan accumulation by dispossession yang digagas oleh David Harvey (2003), kita akan melihat bahwa proyek-proyek ini tak jarang mengarah pada pengambilalihan tanah, sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat lokal untuk kepentingan segelintir pihak.
David Harvey mengemukakan konsep accumulation by dispossession, yaitu proses akumulasi kekayaan di satu pihak yang terjadi dengan cara menguasai dan merampas sumber daya milik pihak lain. Proses ini sering kali dilakukan dengan mengorbankan masyarakat lokal yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, terdapat beberapa mekanisme utama yang menjadi ciri khas accumulation by dispossession. Pertama, penggusuran masyarakat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur berskala besar, seperti bendungan, jalan raya, dan kawasan industri. Kedua, pengambilalihan atau perampasan tanah dengan dalih pembangunan yang diklaim sebagai bagian dari upaya modernisasi dan kemajuan. Ketiga, restrukturisasi kebijakan melalui deregulasi ekonomi dan liberalisasi pasar, yang secara tidak langsung merugikan masyarakat kecil dan komunitas lokal.
Hal ini juga senada dengan Paradigma new-developmentalism, sebagaimana dijelaskan oleh Warburton (2016), menyoroti fenomena pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran, sering kali disertai dengan deregulasi kebijakan yang melemahkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kecil. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak hanya menjadi instrumen modernisasi, tetapi juga menjadi alat legitimasi bagi penguasaan sumber daya atas nama efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Siti Maimunah (2021) menegaskan pula bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkan negara cenderung memutus keterikatan masyarakat terhadap tanah mereka. Atas nama pembangunan, kebijakan-kebijakan tersebut memungkinkan negara untuk mengklaim tanah rakyat sebagai tanah negara, sehingga menghilangkan hak kepemilikan dan kontrol masyarakat terhadap ruang hidup mereka. Proses ini tidak hanya menegaskan dominasi negara dan korporasi, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial yang meminggirkan kelompok rentan.
Dalam konteks Indonesia, beberapa proyek besar yang sedang digalakkan pemerintah seperti proyek Food estate di berbagai wilayah seperti di Merauke, maupun Kalimantan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, justru berisiko besar mengarah pada pengambilalihan lahan milik masyarakat adat dan petani lokal. Tanah yang sebelumnya dikelola secara kolektif oleh masyarakat adat bisa dengan mudah berubah menjadi lahan pertanian berskala besar yang dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat setempat dalam keputusan tersebut.
Hal serupa juga terjadi dalam proyek transisi energi terbarukan. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, berambisi untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga panas bumi. Namun, proyek-proyek ini seringkali membutuhkan pengalihan penggunaan lahan yang mengancam mata pencaharian komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Sumber daya yang sebelumnya dikelola secara lokal dan kolektif kini dikuasai oleh perusahaan besar yang didukung oleh kebijakan negara, tanpa memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Tanah kemudian dilihat hanya sebagai komoditas. Fuentes dkk (2021) mendefinisikan tempat-tempat pengambilalihan ini sebagai “zona pengorbanan” sebagai wilayah yang telah terdegradasi secara lingkungan dan di mana kualitas hidup masyarakat setempat secara signifikan dikompromikan atas nama kemajuan dan akumulasi modal. Istilah ini mencerminkan suatu bentuk kekerasan spasial yang merusak, di mana wilayah-wilayah tertentu dianggap dapat dikorbankan demi manfaat yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi, kemakmuran nasional, atau kemandirian energi.
Begitu pula dengan proyek pariwisata super prioritas yang tengah digalakkan pemerintah seperti di Labuan Bajo. Yesaya Sandang (2023) menyebutkan bahwa Pendekatan pariwisata ditandai dengan model kerangka kerja yang di dominasi dan dipimpin oleh sektor swasta/industri dan pemerintah yang bergerak dari atas ke bawah. Ia juga menyebutkan bahwa rezim pariwisata berkelanjutan cenderung melihat pariwisata sebagai industri, yang pada akhirnya memprioritaskan intervensi yang terpusat, terstandarisasi, dan tersegmentasi. Proyek-proyek pariwisata ini juga mengarah pada privatisasi ruang publik. Tanah dan wilayah yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertani kini diubah menjadi tempat yang dikuasai oleh investor besar dan korporasi yang berfokus pada keuntungan finansial. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal tidak lagi memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk hidup.
Namun, di tengah tantangan tersebut, ada sebuah pendekatan yang dapat memberikan arah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dalam pembangunan: Pembangunan Berbasis Hak (Rights-based Development). Pendekatan ini menempatkan hak-hak manusia, terutama hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk hidup layak, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sebagai prinsip dasar dalam setiap proyek pembangunan.
Pembangunan berbasis hak berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama mereka yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan. Dalam konteks proyek-proyek besar seperti Food estate, Bioethanol, proyek transisi energi terbarukan, dan pariwisata super prioritas, pendekatan berbasis hak ini dapat memberikan solusi dengan memastikan bahwa hak atas tanah dan hak masyarakat adat dihormati. Sebagai contoh, proyek food estate seharusnya tidak sekadar melibatkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat lokal tidak kehilangan akses terhadap tanah mereka tanpa kompensasi yang adil. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat mengurangi konflik dan ketimpangan sosial yang mungkin muncul.
Selain itu, proyek energi terbarukan harus dikembangkan dengan memperhatikan hak atas lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Transisi energi tidak seharusnya hanya menguntungkan perusahaan energi besar, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam sektor energi baru ini, misalnya melalui model pembangkit energi lokal yang mengedepankan keadilan dan keberlanjutan.
Dalam sektor pariwisata, penerapan pendekatan pembangunan berbasis hak dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan yang sering terjadi akibat privatisasi ruang. Proyek-proyek pariwisata seharusnya tidak hanya menguntungkan investor besar, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal sebagai tuan rumah destinasi wisata. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma menuju pengelolaan yang lebih adil dan inklusif, di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama yang berkontribusi dan menikmati manfaat langsung dari pariwisata.
Sebagai alternatif terhadap model pariwisata eksploitatif yang sering mengabaikan keutuhan lingkungan dan budaya, konsep pariwisata regeneratif menjadi solusi korektif yang menekankan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini menempatkan pelestarian ekosistem dan warisan budaya sebagai inti dari pembangunan pariwisata, sembari memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Masyarakat lokal tidak hanya perlu dilibatkan secara aktif, tetapi juga diberikan hak penuh atas pengelolaan sumber daya alam di sekitar mereka, sehingga mereka memiliki kendali atas masa depan ruang hidup mereka.
Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk mengelola dan memperoleh manfaat yang adil dari sektor pariwisata menjadi krusial. Sebagaimana ditegaskan oleh Bellato et al. (2022), pemberdayaan masyarakat melalui kepemilikan hak atas sumber daya alam adalah langkah penting untuk mencegah marginalisasi mereka dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata berbasis hak dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial, menjadikannya instrumen nyata untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Proyek-proyek besar yang tengah dilaksanakan di Indonesia harus mampu menjawab tantangan besar: apakah mereka memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, atau justru mengarah pada pengambilalihan hak-hak masyarakat demi kepentingan segelintir pihak? Pembangunan Berbasis Hak menawarkan jalan keluar dengan menempatkan hak-hak manusia sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya dilihat sebagai akumulasi kekayaan atau kemajuan ekonomi semata, tetapi juga sebagai upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial, lingkungan yang sehat, dan hak-hak dasar bagi semua orang, terutama mereka yang paling rentan.
Indonesia harus memastikan bahwa proyek-proyek besar ini tidak mengarah pada perampasan tetapi justru menjadi alat pemberkuasaan (empower-ment) bagi masyarakat lokal, yang pada akhirnya akan memperkuat keadilan sosial dan keberlanjutan Pembangunan yang adil.
Penulis : Martin Dennise Silaban (Peneliti di SHEEP Indonesia Institute &Mahasiswa Magister Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM)










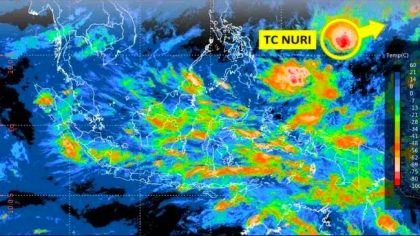







Komentar