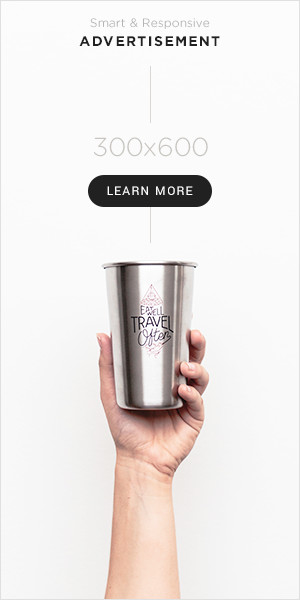Oleh: Martin Dennise Silaban*
Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar penting dalam melindungi hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat yang sering menjadi subjek pembangunan di Indonesia. Salah satu instrumen HAM yang digunakan adalah Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan), yang diadaptasi dari prinsip internasional Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Padiatapa bertujuan memastikan masyarakat adat dapat memberikan persetujuan yang bebas, terinformasi, dan tidak terburu-buru terhadap proyek pembangunan termasuk melalui proyek Transisi Energi seringkali berdampak pada tanah, wilayah, dan kehidupan mereka. Namun, dalam praktiknya, Padiatapa kerap menjadi alat formalitas yang justru melanggengkan ketidakadilan.
Problematika Padiatapa
Prinsip FPIC, sebagaimana termaktub dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), berkomitmen menjamin hak masyarakat adat untuk menyetujui atau menolak proyek pembangunan. Elemen “bebas” memastikan tidak ada paksaan atau tekanan dalam proses persetujuan, sementara “sebelumnya” berarti keputusan harus dibuat jauh sebelum proyek dimulai. Aspek “terinformasi” mewajibkan semua pihak menyediakan informasi yang dapat dipahami, dan “persetujuan” menegaskan hak masyarakat adat untuk membuat keputusan berdasarkan mekanisme mereka sendiri. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini jauh dari ideal.
Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur implementasi Padiatapa. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum nasional sering kali tidak sinkron dengan standar internasional. Ketidakselarasan ini membuka ruang bagi interpretasi sepihak oleh pemerintah dan perusahaan, yang lebih sering mengutamakan kepentingan mereka. Proses persetujuan yang seharusnya melindungi masyarakat adat justru menjadi alat legitimasi pembangunan yang mengabaikan hak-hak mereka.
Lebih lanjut, ketimpangan kekuatan dalam negosiasi antara masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya memperburuk situasi. Pemerintah dan perusahaan memiliki sumber daya hukum, ekonomi, dan politik yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat adat, sehingga posisi tawar masyarakat menjadi sangat lemah. Kondisi ini diperburuk oleh perbedaan budaya dan cara pandang antara kedua belah pihak. Bagi masyarakat adat, persetujuan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan hak yang berkaitan dengan kedaulatan, identitas budaya, dan penentuan nasib sendiri.
Ketergantungan ekonomi masyarakat adat terhadap proyek pembangunan juga sering kali menjadi tekanan yang sulit dielakkan. Kondisi ini menggambarkan apa yang disebut Peter Benson dan Stuart Kirsch sebagai politics of resignation, yakni situasi di mana masyarakat adat menerima dampak buruk pembangunan demi mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Meskipun menyadari risiko yang ditimbulkan, ketergantungan pada manfaat ekonomi membuat mereka berada dalam posisi terpaksa menerima kebijakan yang merugikan.
Dekolonisasi Hak Asasi Manusia
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pendekatan dekolonisasi yang ditawarkan Abdullahi Ahmed An-Na’im melalui bukunya berjudul Decolonizing Human Rights memberikan jalan keluar yang relevan. Dekolonisasi HAM menurut An-Na’im bukan berarti menolak universalitas HAM, tetapi menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan konteks lokal, termasuk budaya, nilai, dan sistem sosial masyarakat yang menjadi subjeknya. Pendekatan ini mendesak kita untuk merekontekstualisasi instrumen seperti Padiatapa agar tidak hanya menjadi terjemahan prosedural dari konsep internasional, tetapi benar-benar berakar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.
An-Na’im menekankan bahwa dekolonisasi HAM membutuhkan reformasi mendasar dalam kerangka hukum dan kebijakan. Hukum nasional harus dirancang untuk memperkuat posisi masyarakat adat, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan lain. Ini berarti memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai pelaksanaan Padiatapa, termasuk memastikan bahwa persetujuan benar-benar mencerminkan keputusan independen masyarakat adat. Dengan pendekatan ini, hukum dapat menjadi instrumen yang melindungi masyarakat adat dari tekanan eksternal dan manipulasi.
Selain itu, An-Na’im menyoroti pentingnya memberdayakan masyarakat adat dalam proses negosiasi. Ketimpangan kekuatan yang ada harus diatasi dengan menyediakan pendidikan hukum, pelatihan advokasi, dan pendampingan yang memungkinkan masyarakat adat memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi secara setara. Penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat adat serta metode komunikasi yang menghormati budaya lokal juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini.
Dekolonisasi menurut An-Na’im juga berarti menghormati pandangan dunia (worldview) masyarakat adat, termasuk cara mereka memahami persetujuan. Ia mengusulkan pendekatan yang memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendefinisikan HAM berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai mereka sendiri, bukan sekadar menerima konsep yang diimpor dari luar. An-Na’im berpendapat bahwa universalisme HAM sering kali didasarkan pada nilai-nilai dan pengalaman sejarah global-north, yang tidak selalu relevan atau cocok dengan konteks budaya dan sejarah masyarakat di global-south termasuk Indonesia. Bagi masyarakat adat, persetujuan adalah bagian dari kedaulatan dan identitas budaya, bukan sekadar langkah administratif. Oleh karena itu, proses Padiatapa harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai ini, dengan melibatkan dialog yang setara dan transparan.
Pendekatan An-Na’im juga menggarisbawahi pentingnya mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat adat terhadap proyek pembangunan. Pemerintah dan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat adat, sehingga mereka tidak merasa terpaksa menyetujui proyek yang merugikan mereka. Alternatif ekonomi ini harus dirancang untuk mendukung kemandirian masyarakat adat dalam jangka panjang, sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
Dekolonisasi HAM, sebagaimana diusulkan Abdullahi Ahmed An-Na’im, memberikan pendekatan strategis untuk mereformasi Padiatapa. Dengan menyesuaikan prinsip-prinsip HAM dengan konteks lokal, memperkuat posisi masyarakat adat, dan mengatasi ketimpangan struktural, Padiatapa dapat menjadi instrumen yang benar-benar melindungi hak-hak masyarakat adat. Dekolonisasi bukan hanya tentang menyesuaikan HAM dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat adat untuk menentukan masa depan mereka secara mandiri dan bermartabat.
*Mahasiswa Magister Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM & Peneliti di SHEEP Indonesia Institute