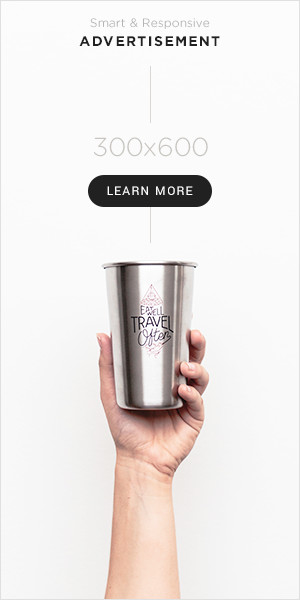JAKARTA – Ekspansi praktik agro-ekstraktif di Tanah Papua kian menunjukkan dampak sosial dan ekologis yang serius. Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Pusaka Bentala Rakyat, yang mendiseminasikan dua hasil riset dan dokumentasi penelitian terkait perluasan industri berbasis sumber daya alam di Papua.
Diskusi ini menjadi ruang dialog terbuka antara periset, pegiat advokasi, dan masyarakat adat untuk membedah konsekuensi pembangunan yang bertumpu pada perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan skala besar—sektor yang dinilai membawa risiko tinggi bagi keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal.
Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Desmiwati, menegaskan bahwa pengembangan perkebunan sawit di Papua tidak dapat disamakan dengan wilayah lain di Indonesia.
Kompleksitas persoalan tanah adat, kerentanan sosial, serta nilai ekologis Papua yang sangat tinggi menuntut pendekatan pembangunan yang jauh lebih hati-hati dan inklusif.
“Pengembangan ekonomi di Papua harus dilakukan secara humanis dan berkeadilan, agar tidak justru memperdalam ketimpangan sosial dan konflik,” ujar Desmiwati dalam diskusi hybrid yang berlangsung di Auditorium Gedung Widya Graha BRIN, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Rabu (28/1).
Ia menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk perlindungan hak atas tanah dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Sementara itu, Peneliti BRIN Lukas Rumboko Wibowo mengungkapkan bahwa Papua kini menjadi sasaran utama ekspansi industri kayu, menyusul menipisnya hutan di Kalimantan dan Sumatra akibat eksploitasi besar-besaran.
Di wilayah adat Moi, Kabupaten dan Kota Sorong, ekspansi industri kehutanan dinilai telah memicu perampasan tanah adat, konflik sosial, serta ketimpangan ekonomi yang tajam.
Menurut Lukas, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat adat jauh dari sebanding dengan nilai ekspor kayu yang dihasilkan.
“Yang tersisa bagi masyarakat lokal justru kerusakan hutan dan konflik berkepanjangan,” ujarnya.
Dari perspektif advokasi, Franky Samperante menyoroti masih maraknya pelanggaran hak masyarakat adat dalam pengembangan industri ekstraktif, khususnya perkebunan kelapa sawit. Lemahnya penerapan prinsip free, prior and informed consent (FPIC) membuat banyak komunitas adat tidak mengetahui wilayahnya telah masuk konsesi perusahaan.
Akibatnya, kompensasi yang diterima sangat minim, sementara dampak sosial—mulai dari konflik internal hingga hilangnya sumber penghidupan—kian meluas.
Kesaksian langsung datang dari Desi Mansinau, perwakilan masyarakat adat, yang menyampaikan bahwa janji kesejahteraan melalui skema kebun plasma tak pernah terealisasi.
Alih-alih sejahtera, masyarakat justru terjerat utang dan kehilangan kendali atas tanah adat mereka.
“Sawit tidak membawa kesejahteraan bagi kami. Yang datang justru penderitaan,” tegas Desi.
Melalui diskusi ini, BRIN menegaskan pentingnya pembangunan berbasis riset yang berkeadilan, menghormati hak masyarakat adat, serta menjaga keberlanjutan ekologis Papua—wilayah yang selama ini menjadi benteng terakhir hutan tropis Indonesia. (TR Network)