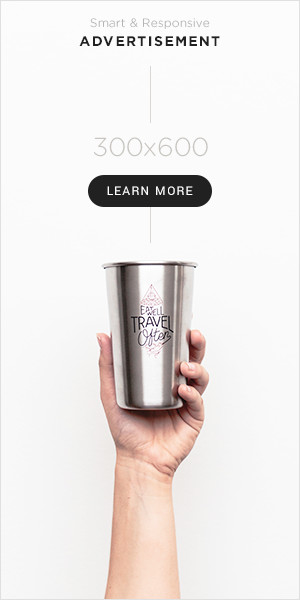JAKARTA – Di tengah tren global yang mulai meninggalkan batu bara, laporan terbaru Global Energy Monitor (GEM) justru mengungkapkan bahwa Indonesia masih agresif membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terutama yang bersifat captive. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar soal konsistensi komitmen Indonesia terhadap transisi energi dan target emisi nol bersih (net zero emissions).
Dalam laporan “Boom and Bust Coal 2025: Tracking the Global Coal Plant Pipeline”, GEM mencatat bahwa pertumbuhan kapasitas PLTU global tahun lalu mencapai titik terendah dalam dua dekade terakhir—hanya 44 gigawatt (GW), jauh di bawah rata-rata tahunan 72 GW selama 2004–2024.
Namun, Indonesia justru menempati posisi ketiga dunia dalam penambahan kapasitas PLTU sebesar 1,9 GW pada tahun 2024. Sebanyak 80 persen kapasitas tersebut merupakan PLTU captive, yakni pembangkit listrik yang dibangun untuk kebutuhan industri sendiri, khususnya sektor hilirisasi mineral.
GEM mencatat saat ini terdapat 130 unit PLTU captive di Indonesia dengan kapasitas minimal 30 megawatt (MW), serta 21 unit lainnya dalam tahap konstruksi dan pra-konstruksi. Kapasitas PLTU captive Indonesia melonjak dari 5,5 GW pada 2019 menjadi 16,6 GW pada 2024—lonjakan tiga kali lipat dalam waktu lima tahun.
Lonjakan ini didorong oleh program hilirisasi mineral nasional yang membutuhkan pasokan energi besar dan stabil, namun berbasis batu bara.
Sejak Perjanjian Paris 2015, kapasitas PLTU Indonesia meningkat sebesar 29 GW. Kini, Indonesia menempati posisi kelima dunia dengan kapasitas PLTU terbesar, mencapai 54,7 GW.
Dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060, Indonesia bahkan merencanakan penambahan kapasitas PLTU sebesar 26,7 GW dalam tujuh tahun ke depan, 75 persen di antaranya adalah PLTU captive.
Peneliti Senior GEM, Lucy Hummer, menyoroti adanya kontradiksi antara komitmen iklim Indonesia dan kebijakan batu baranya.
“Terdapat ketidaksesuaian antara rencana batu bara Indonesia dan komitmen iklimnya. Ini seperti tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan,” ujarnya, Sabtu (11/4/2025).
Meski pemerintah Indonesia menyatakan moratorium pembangunan PLTU baru setelah 2022, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk proyek yang sudah masuk dalam perencanaan PLN atau PLTU yang mendukung proyek strategis nasional.
Pengembangan PLTU captive berisiko mengulang kesalahan masa lalu, yakni kelebihan kapasitas pembangkit, perjanjian jangka panjang yang mahal, dan tekanan terhadap lingkungan serta masyarakat.
“PLTU captive berkembang tanpa kendali. Bahkan, organisasi keagamaan, usaha kecil, hingga kampus kini bisa mendapat dana dari batu bara,” ungkap Zakki Amali, Manajer Riset Trend Asia. Ia memperingatkan bahwa Indonesia berada di ambang kegagalan transisi energi jika eksploitasi batu bara terus meningkat.
Pemerintah masih menjadwalkan operasi PLTU hingga 2060 dengan mengandalkan teknologi co-firing, carbon capture and storage (CCS), hingga retrofit untuk amonia, biomassa, bahkan nuklir. Namun, GEM menilai strategi ini tidak efisien dan memiliki efektivitas pengurangan emisi yang rendah.
“Co-firing dengan biomassa bisa mendorong deforestasi, sementara CCS masih merupakan solusi yang belum terbukti,” tambah Lucy.
Dunia Tinggalkan Batu Bara, Indonesia Masih Bertahan
Sebanyak 22 negara telah memangkas kapasitas PLTU batu bara mereka, dengan Uni Eropa menghentikan operasi sebesar 11 GW pada 2024—naik empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Jerman menjadi kontributor terbesar dengan 6,7 GW, sedangkan Inggris menjadi negara keenam yang sepenuhnya menghentikan penggunaan batu bara.
Di sisi lain, Indonesia bersama China, India, dan sembilan negara lain justru menambah kapasitas PLTU mereka. China memimpin dengan penambahan 30,52 GW, diikuti India (5,81 GW), Indonesia (1,9 GW), Bangladesh (1,26 GW), dan Korea Selatan (1,05 GW). (TR Network)